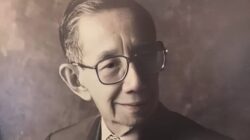Oleh: Prof. Herman Agustiawan, Ph.D
Pakar Ketahanan Energi
Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2014
Pendiri Prodi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan (UNHAN)
Era disrupsi energi membawa perubahan signifikan dalam sistem energi yang mengubah cara energi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari inovasi teknologi hingga dinamika global yang mempercepat pergeseran dari dominasi energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT).
Seiring dengan meningkatnya efisiensi dan penurunan biaya teknologi energi bersih, transisi menuju EBT menjadi kebutuhan global. Diversifikasi energi menjadi strategi penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi.
Kemajuan teknologi menjadi kunci dalam optimalisasi pemanfaatan EBT. Teknologi penyimpanan energi, seperti baterai berbasis nikel dan sistem penyimpanan energi lainnya, menjadi krusial dalam meningkatkan stabilitas pasokan listrik dari sumber terbarukan. Digitalisasi melalui smart grid dan kecerdasan buatan (AI) mampu meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi.
AI dapat mengoptimalkan jaringan listrik, memprediksi permintaan energi, serta meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi listrik. Hidrogen hijau juga menjadi solusi potensial dalam mendukung dekarbonisasi industri berat, sektor transportasi, dan penyimpanan energi skala besar. Diproduksi melalui elektrolisis air menggunakan listrik dari EBT, hidrogen hijau tidak menghasilkan emisi karbon.
Indonesia, dengan potensi EBT yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekosistem hidrogen hijau yang kompetitif.
Dukungan regulasi, insentif bagi investor, serta reformasi subsidi energi menjadi faktor penentu percepatan transisi energi ini. Kemitraan sektor publik dan swasta juga berperan penting dalam memperkuat ekosistem EBT dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di pasar energi hijau global. Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 1600 hingga saat ini, sistem energi mengalami transformasi besar.
Biomassa dan migas mendominasi hingga tahun 1950-an, sebelum akhirnya reaktor nuklir mulai dimanfaatkan di Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perkembangan EBT semakin pesat sejak 1980-an, ditandai dengan pengembangan panel surya dan turbin angin di negara maju. Tahun 2000-an menjadi awal era transisi energi dengan penurunan harga panel surya dan turbin angin.
Percepatan terjadi pada 2010-an dengan kehadiran mobil listrik (Tesla) serta kebijakan energi hijau di berbagai negara. Dekade 2020-an menjadi era inovasi lebih lanjut dengan pengembangan hidrogen hijau, baterai penyimpanan besar, dan teknologi smart grid.
Negara-negara maju telah lama mendominasi riset dan inovasi EBT berkat investasi besar selama puluhan tahun. Mereka berhasil mengembangkan teknologi hingga tahap komersialisasi dan kini mencari pangsa pasar, termasuk di Indonesia. Namun, ketergantungan pada teknologi impor membuat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian energi.
Salah satu faktor utama yang menghambat inovasi energi dalam negeri adalah minimnya investasi dalam riset. Selama puluhan tahun, anggaran riset Indonesia tidak pernah mencapai 1% dari APBN, bahkan hanya berkisar di bawah 0,3% dari PDB. Angka ini jauh dari rekomendasi UNESCO sebesar 1% dan tertinggal dari negara lain seperti Malaysia (1,15%), Singapura (2,07%), China (2,1%), dan Jepang (3,65%).
Minimnya dana riset menghambat kemampuan Indonesia dalam mengembangkan teknologi energi sendiri. Alih-alih berinvestasi dalam inovasi, banyak pelaku bisnis lebih memilih keuntungan instan dengan mengimpor teknologi asing. Proses nilai tambah dari inovasi anak bangsa pun tersendat karena kurangnya dukungan sistem tata-niaga nasional dan global.
Kondisi ini semakin diperparah dengan pembubaran lembaga riset seperti LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN, yang dilebur ke dalam BRIN melalui Perpres No. 33 Tahun 2021. Meski bertujuan untuk memperkuat riset nasional, kebijakan ini justru memangkas anggaran dan memicu kekhawatiran di kalangan akademisi serta peneliti.
Transisi energi global juga sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Misalnya, ketika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris pada 2025. Kebijakan ini mencerminkan preferensi AS untuk meningkatkan produksi bahan bakar fosil ketimbang mengembangkan energi hijau. Namun, di sisi lain, Uni Eropa tetap berkomitmen pada European Green Deal dengan target netralitas karbon pada 2050.
Sementara itu, China terus berinvestasi besar-besaran dalam EBT, meskipun masih bergantung pada batu bara. Dunia pun berpotensi terbagi menjadi tiga blok energi: AS yang berfokus pada migas, China yang mengembangkan EBT secara masif, dan Uni Eropa yang berada di tengah dengan sikap menunggu tetapi tetap mendukung agenda hijau.
Persaingan ini semakin menegaskan bahwa sumber EBT, baterai, hidrogen hijau, dan AI akan menjadi faktor utama dalam lanskap energi masa depan. Negara yang unggul dalam teknologi ini akan memimpin, sementara yang tertinggal hanya akan menjadi konsumen. Bagi Indonesia, strategi transisi energi tidak bisa hanya bergantung pada pasar global.
Dengan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia berpotensi menjadi pusat utama produksi baterai kendaraan listrik dunia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan jaringan gas kota (city gas) dapat meningkatkan efisiensi distribusi energi.
Pemerintah juga perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor LNG dan LPG dengan mempercepat pembangunan infrastruktur energi domestik. Seperti halnya pasokan air PDAM yang mengalir ke rumah-rumah, distribusi gas kota juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi energi di perkotaan.
Sejarah menunjukkan bahwa negara dengan penguasaan teknologi energi lebih diuntungkan daripada negara pengekspor sumber daya mentah. Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia harus meningkatkan anggaran riset dan memastikan inovasi teknologi lokal dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata-niaga nasional maupun global.
Negara-negara maju berhasil menguasai teknologi energi karena investasi besar dalam riset dan inovasi. Indonesia harus belajar dari pengalaman ini dengan mendorong regulasi yang memberi insentif bagi perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan teknologi energi lokal. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk impor tanpa mampu bersaing dalam industri energi global.
Tanpa inovasi, Indonesia hanya bisa menjadi penonton dalam persaingan energi dunia. Namun, kita masih punya pilihan: tetap diam dan menyaksikan, atau bangkit dan menjadi pemain utama dalam peta energi masa depan.